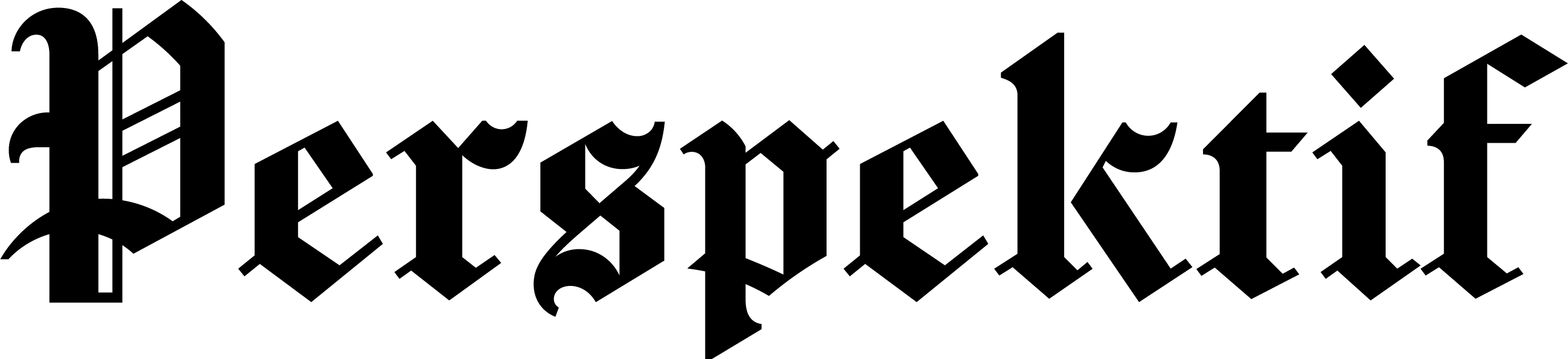Penulis: Reza Habsyi, Founder, Ruang Nalar Merdeka (RNM)
Dalam beberapa dekade terakhir, neurosains tampil sebagai cabang ilmu paling prestisius dalam menjelaskan hakikat manusia. Berkat kecanggihannya membaca aktivitas otak lewat citra MRI dan eksperimen neuropsikologi, sebagian ilmuwan mulai mengklaim bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki kehendak bebas (free will).
Kesadaran, moralitas, bahkan cinta dianggap hanya sebagai hasil aktivitas neuron yang deterministik atau serangkaian proses elektrokimia tanpa ruang bagi jiwa, nurani, atau kebebasan.
Tokoh seperti Francis Crick, peraih Nobel penemu struktur DNA, dengan lugas menyatakan:
“Kamu, kegembiraan dan kesedihanmu, ingatan dan ambisimu, rasa identitas dan kehendak bebasmu sesungguhnya tak lain hanyalah perilaku dari sekumpulan besar sel-sel saraf.”(The Astonishing Hypothesis, 1994)
Senada, Sam Harris dalam bukunya Free Will (2012) menegaskan bahwa kehendak bebas hanyalah ilusi. Menurutnya, setiap pikiran, pilihan, dan tindakan manusia sepenuhnya ditentukan oleh sebab-sebab neurobiologis dan lingkungan, bahkan sebelum kita menyadarinya.
Eksperimen Benjamin Libet (1983) dan John-Dylan Haynes (2008) sering dijadikan pembenaran. Keduanya menunjukkan bahwa otak memutuskan sesuatu milidetik sebelum manusia sadar telah memilih.
Pandangan ini melahirkan wajah baru "neurodeterminisme", yakni keyakinan bahwa manusia tak lebih dari robot biologis yang bergerak sesuai pola neuralnya. Moralitas hanyalah strategi evolusioner, dan spiritualitas hanyalah simulasi kimia. Kesadaran manusia direduksi menjadi sistem mekanik tanpa substansi transenden.
Implikasi Moral dan Sosial dari Manusia Tanpa Kehendak Bebas
Namun bila demikian, apa arti nilai, moral, dan agama? Jika manusia sepenuhnya dikendalikan oleh struktur otaknya, maka konsep tentang kebaikan, kejahatan, dosa, pahala, atau tanggung jawab moral menjadi kehilangan makna. Etika dan hukum hanyalah ilusi sosial yang dibangun di atas mekanisme biologis yang buta nilai.
Kita pun harus bertanya secara radikal: Jika manusia tidak memiliki kehendak bebas, lalu untuk apa kita berbicara tentang tanggung jawab moral?
Bayangkan, bila seseorang melakukan kekerasan atau korupsi, lalu dianggap semata hasil dari struktur otak kriminal atau gen psikopatik, maka hukuman moral menjadi tidak relevan. Dalam logika neurodeterminisme, pelaku tidak bersalah karena ia hanyalah produk dari rangkaian sebab biologis yang tidak dapat ia kendalikan.
Aspek ini membawa konsekuensi besar bagi konsep hukum modern. Hukum hanya berlaku bagi manusia yang dianggap memiliki kemampuan memilih antara baik dan buruk, karena dasar hukumnya adalah tanggung jawab individu. Di praktik hukum Indonesia, misalnya, seseorang dapat dianggap tidak bertanggung jawab jika kehilangan kapasitas memilih akibat gangguan jiwa atau tekanan ekstrem (KUHP Pasal 44–48).
Pertanyaannya, bagaimana dengan kasus ekstrem, seperti psikopat atau pelaku kekerasan seksual, jika dikatakan bahwa perilaku mereka hanyalah ekspresi genetik dan neurokimia tertentu? Apakah penyelesaiannya cukup dengan operasi otak atau terapi obat penenang untuk “menormalisasi” perilaku?
Paradigma ini, jika diterapkan secara ekstrem, mengubah hukum menjadi proyek teknokratis, bukan lagi forum moral, tetapi sekadar soal manajemen biologis manusia melalui intervensi medis.
Di titik ini, Sam Harris mencoba menjawab kritik tersebut.
Menurutnya, menolak kehendak bebas tidak berarti menolak moralitas. Ia menyatakan bahwa pemahaman deterministik justru membuka ruang bagi belas kasih dan keadilan yang lebih rasional, sebab kita bisa melihat pelaku kejahatan bukan sebagai “pendosa jahat” yang pantas dibenci, melainkan sebagai individu yang otaknya rusak oleh sebab biologis dan sosial tertentu.
Dengan begitu, hukuman seharusnya bukan untuk membalas, tetapi untuk mencegah bahaya dan merehabilitasi.
“Knowing that people are not free to choose their actions can allow us to feel compassion rather than hatred.”
— Sam Harris, Free Will (2012)
Namun argumen ini menyisakan paradoks mendasar. Jika semua tindakan hanyalah hasil proses otak tanpa pilihan, maka siapa yang harus menumbuhkan belas kasih itu? Apakah belas kasih juga sekadar keluaran deterministik dari jaringan neuron tertentu?
Harris tidak menjawab problem moral, ia hanya memindahkan tanggung jawab dari manusia ke mekanisme otak, lalu menamai hasilnya sebagai kebajikan rasional.
Lebih jauh, determinisme biologis berpotensi menumbuhkan bentuk baru superioritas genetik.
Jika kecerdasan, moralitas, atau kecenderungan kejahatan dianggap hasil struktur otak, maka manusia bisa diklasifikasikan berdasarkan kualitas neural. Di titik ini, rasisme yang dulu melegitimasi kolonialisme dan eugenika dapat hidup kembali dalam bentuk modern, diskriminasi berdasarkan hasil pemindaian otak atau profil genetik.
Mereka yang otaknya dianggap ideal dipuja sebagai manusia unggul, yang lainnya direduksi menjadi cacat biologis. Inilah sisi gelap dari sains yang kehilangan etika ketika manusia dijadikan objek ukur, bukan subjek bermartabat.
Sejarah pernah memperingatkan. Pada era Nazi, rezim Hitler mendorong orang-orang ‘ras Arya’ untuk saling kawin agar lahir bayi-bayi yang dianggap unggul, sementara mereka yang dinilai cacat genetik disterilkan atau dieliminasi. Logika yang sama kini bisa muncul kembali, bukan atas nama ras, melainkan atas nama sains menilai manusia dari anatomi otaknya, bukan martabatnya.
Mengembalikan Sains pada Kemanusian
Masalah utama neurodeterminisme bukan pada sainsnya, melainkan pada hilangnya arah kemanusiaan yang menyertainya. Dalam semangat saintisme, neurosains kadang tampil arogan: meremehkan filsafat, agama, dan disiplin humaniora sebagai tidak ilmiah.
Manusia yang kompleks dengan pengalaman batin, cinta, penderitaan, dan iman, disederhanakan menjadi sekumpulan sinyal listrik dalam otak.
Sains yang semula lahir untuk memahami manusia, justru berbalik menyempitkan manusia.
Ia menyingkirkan dimensi ruhani, makna, dan kebebasan yang membuat manusia menjadi manusia.
Kritik terhadap neurodeterminisme bukanlah penolakan terhadap neurosains itu sendiri, melainkan penolakan terhadap pemutlakan.
Ilmu tentang otak penting dan mulia tetapi ketika ia mengklaim mampu menjelaskan seluruh realitas manusia, ia berubah menjadi ideologi.
Padahal manusia bukan sekadar otak, ia adalah kesadaran yang mampu menilai, mencinta, dan menolak nalurinya sendiri.
Dalam pandangan spiritual dan filosofis, kebebasan bukan sekadar ilusi, melainkan inti eksistensi manusia. Selama manusia masih bisa menolak dorongan biologisnya demi nilai yang ia yakini, di situlah letak kemanusiaannya yang sejati.
Neurosains deterministik, dengan segala klaim kemajuannya, sedang menggiring kita menuju dunia tanpa tanggung jawab, tanpa moral, dan tanpa jiwa. Jika manusia hanyalah mesin biologis, maka tidak ada lagi dasar bagi hukum, keadilan, dan bahkan cinta.
Maka tugas kita bukan menolak sains, tetapi mengembalikan sains pada kemanusiaannya agar otak tidak menghapus jiwa, dan pengetahuan tidak menyingkirkan kebijaksanaan.
Reza Habsyi adalah pendiri Ruang Nalar Merdeka (RNM), komunitas dan pusat kajian independen yang berfokus pada pengembangan pemikiran kritis, filsafat, politik dan spiritualitas dalam konteks sosial kontemporer