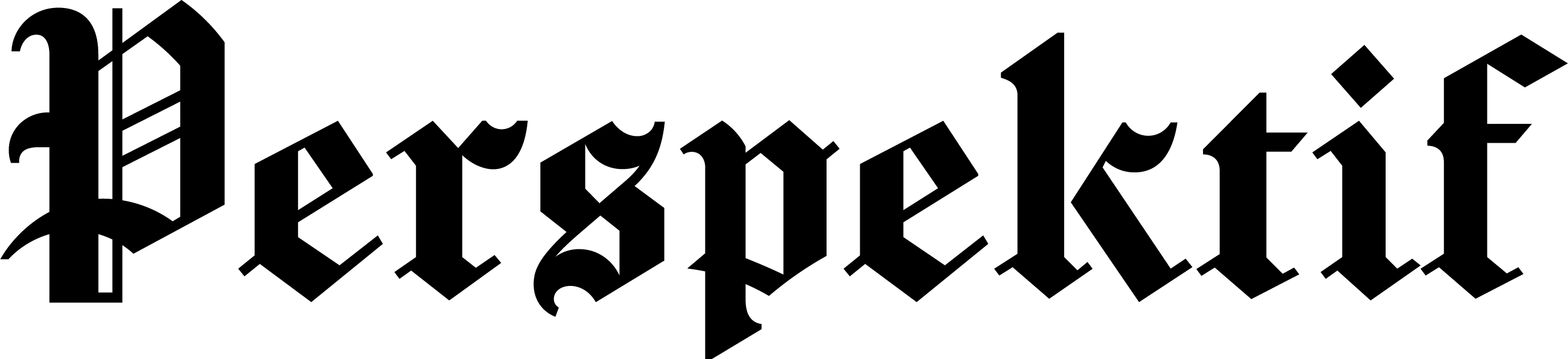Oleh: Reza Habsyi
OPINI - Saya kerap geleng kepala ketika melihat sebagian orang begitu emosional menanggapi adagium René Descartes, filsuf besar asal Prancis, yang terkenal dengan ungkapannya: “Cogito ergo sum” aku berpikir maka aku ada.
Bagi sebagian kalangan, khususnya pengikut filsafat eksistensialis, adagium itu langsung dimentahkan dengan semboyan lain: eksistensi mendahului esensi. Sementara para pegiat filsafat Islam juga tak kalah lantang melontarkan bantahan.
Mereka mengutip Mulla Sadra dan teori wujud untuk menyodorkan versi tandingan: “Aku ada, maka aku berpikir.” Argumennya sederhana, bagaimana mungkin berpikir tanpa adanya subjek yang sudah eksis? Dengan kata lain, bukan berpikir yang menjamin keberadaan, melainkan keberadaanlah yang memungkinkan berpikir.
Namun, menurut saya, adagium Descartes ini tidak sepatutnya dilihat semata dalam kerangka ontologis. Ada baiknya kita membacanya lebih bijak sebagai pernyataan filosofis yang memiliki nilai. “Aku berpikir maka aku ada” bisa dimaknai sebagai dorongan agar manusia hadir secara signifikan di tengah masyarakat melalui daya nalarnya.
Seseorang yang tidak berpikir, tidak kritis, atau tidak memiliki narasi, pada akhirnya tak akan dianggap dalam lingkaran sosialnya. Dalam konteks ini, “ada” tidak lagi berarti sekadar eksistensi fisik, melainkan nilai keberartian dan pengaruh.
Justru dengan adagium itu, Descartes ingin menunjukkan bahwa nilai manusia tidak terletak semata pada keberadaannya secara biologis, melainkan pada esensinya, kemampuan berpikir. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain.
Manusia hadir bukan sekadar ada, melainkan ada dengan kesadaran, refleksi, dan penalaran. Dalam bahasa agama, "afalā ta‘qilūn“ tidakkah kalian berpikir?” seakan menjadi gema yang sejalan dengan semangat Descartes, menjadikan akal budi sebagai penanda utama martabat manusia.
Cogito ergo sum, pada akhirnya adalah tentang makna, tentang visi kesempurnaan yang bukan hanya bicara being (statis) tapi becoming, kehendak yang terus menerus bergerak aktif dan transformatif.
Di titik inilah, berpikir tidak sekadar instrumen logis, melainkan motor peradaban, ia yang membuat manusia mampu keluar dari sekadar “hidup” menuju “menghidupkan”, memberi bentuk pada dunia, dan menorehkan jejak dalam sejarah.
Tapi apapun itu, bagi saya, perdebatan apakah berpikir mendahului ada atau sebaliknya sudah tidak begitu relevan hari ini. Keduanya benar dalam konteks masing-masing, dan tak perlu didikotomikan secara kaku.
Justru yang lebih membuat saya heran, sebagian praktisi filsafat masih saja sibuk menghabiskan energi pada perbincangan ontologis. Mereka membedah “wujud dan esensi”, “substansi dan aksiden”, atau “realitas dan Ada” seolah-olah itu persoalan yang paling mendesak.
Memang, dalam tradisi filsafat, diskursus semacam itu punya tempatnya sendiri. Tapi hari ini, apakah masih relevan ketika dunia kita dihadapkan pada ketidakadilan sosial, krisis politik, hingga ancaman ekologis? Alih-alih memberi pencerahan, diskusi yang terlalu teknis justru sering terdengar seperti jargon kosong dan tidak bersentuhan dengan denyut kehidupan nyata.***